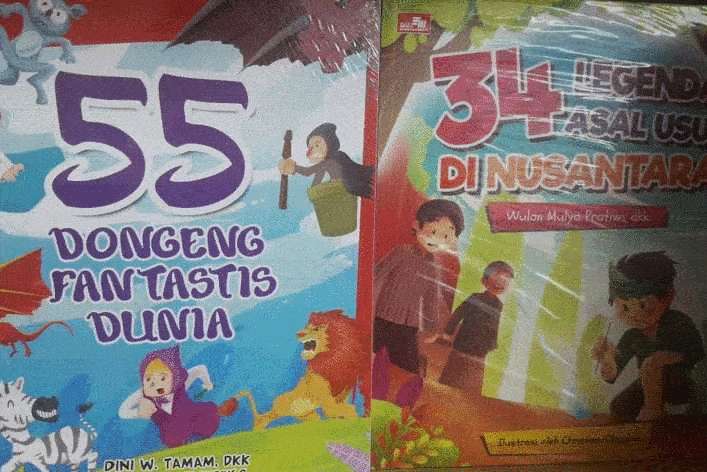Sekuat mungkin butiran bening ini kutahan agar tidak tumpah menjadi tangisan. Pantang bagiku menangis untuk kedua kalinya di hadapan mas Fian. Makin besar saja hidungnya nanti.
Tangan kokoh mas Fian masih erat mencengkeram tangan kiriku. Menahanku agar duduk kembali. Ibu masuk ke dalam dapur. Aku tak bisa berkutik.
"Lepaskan, Mas!" teriakku tertahan.
"Tidak akan aku lepaskan, sebelum kita bicara baik-baik tanpa emosi."
Kutatap mata elangnya. Tak ada tawar menawar dari sorot matanya. Tegas dan memintaku agar duduk kembali. Tubuhku masih menolak ajakannya. Berdiri mematung menatapnya tak berkedip.
"Apa yang akan kita bicarakan? Cepetan, aku mau pulang!"
"Kalau tidak duduk, tak akan kumulai percakapan ini. Duduklah, De!" lembut bicaranya sambil mengusap lenganku. Perlahan namun mampu membuatku duduk. Dia masih meraja di hatiku, tak kuasa aku membangkangnya. Rasa rindu mulai menyergap hatiku. Sekian lama tak bertemu, terakhir adalah pertengkaran hebat kami di ujung telefon.
"Apa yang kau inginkan, De?" tanyamu saat aku menangis hebat di ujung telefon.
Kukatakan dengan emosi yang memuncak. "Aku nggak mau nikah denganmu, Mas!"
Diam tanpa suara. Entah apa yang ada dalam pikirannya kala itu. Padahal acara lamaran akan berlangsung kurang dari seminggu. Dan aku membatalkannya. Tak kuat rasanya harus berlanjut ke jenjang pernikahan jika mas Fian tetap seperti ini. Hatiku lelah menghadapinya.
"Ya sudah kalau memang ingin batal. Aku tinggal bilang ke ibu, untuk tidak jadi melamarmu." putusmu. Dan selesailah kami.
Rencana untuk hidup bersama dalam satu biduk perahu kandas. Sebelumnya memang sudah terjadi perang dingin di antara kami. Mas Fian menyebalkan, menurutku. Tak pernah bisa terbuka setiap ada masalah. Ujung-ujungnya hanya mendiamkanku dalam waktu lama. Tidak pernah mau mengangkat telfonku jika sedang marah. Betah berhari-hari bahkan berminggu-minggu dalam diamnya. Hingga memaksaku menjadi pengemis maafnya jika kami selesai berdebat. Dia nggak pernah memulai kata maaf. Hingga akhirnya aku menangis hebat dan memutuskan untuk membatalkan semuanya.
Ya, masih ingat, ketika aku membatalkan semuanya. Waktu itu mas Fian juga mengiyakan. Tidak berusaha membujukku kembali atau merayu hatiku agar menarik keputusanku. Hingga akhirnya, kami seperti dua orang yang tidak saling kenal. Menjadi asing. Kontak di antara kami terputus.
Harga diriku mengatakan untuk melakukan hal yang sama. Diam tak ingin berkabar. Mas Fian juga enggan sepertinya. Padahal dia masih menjadi raja di hatiku.
Kugigit bibir bawahku tanpa sadar. Mataku lekat menatapa wajah di hadapanku. Wajah yang sangat aku rindukan beberapa minggu ini. Butiran bening sudah terkumpul.
"Kalau Mas ingin ambil rumah yang sudah kita bayar bersama, ambil saja. Aku akan cari kost lagi," lirih suaraku terdengar.
Rumah mungil yang aku dan mas Fian beli, sempat aku kembalikan ke ibu. Namun kata ibu, aku diminta menempati. Sayang dari pada kotor dan rusak nantinya, begitu kata beliau. Aku tidak tahu, apakah mas Fian tahu keputusan ibu.
Terdengar tawa ringan dari mas Fian setelah perkataanku.
"Tempati saja, De. Aku nggak akan memintanya darimu. Aku hanya ingin kita melanjutkan hubungan kita. Kita menikah."
Kutatap wajah yang selalu menghiasi mimpi malamku. Ada kesungguhan dalam kata-katanya. Si kepala batu, begitu julukan adik-adiknya, memintaku melanjutkan rencana yang sudah pernah matang.
Hatiku bimbang. Satu sisi aku begitu ingin menikah dengannya. Sisi hatiku yang lain mengatakan, seandainya aku menikah, bagaimana aku menghadapi aksi diamnya jika sedang marah? Kalau hanya sehari dua hari membisu, tak apa. Tapi ini?
Kepalaku menggeleng lemah. Ada ketakutan terbesar dalam hidupku. Menikah dengan orang yang asyik dalam dunia diamnya. Tidak!
"Kau masih marah denganku, De? Hingga menolak menikah denganku?"
Oh, tak tega aku mendengarnya. Hatiku dibuat bingung.
Bersambung.
#OneDayOnePost